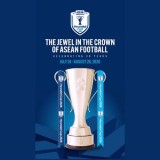TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional pada 2010, sebagian masyarakat menyambut dengan haru. Namun sebagian lain bertanya: apakah penghargaan itu datang karena jasa politiknya, peran keagamaannya, atau kebesaran moralnya?
Pertanyaan ini tak sekadar retoris. Ia menyentuh inti persoalan: bagaimana bangsa ini menafsirkan makna “pahlawan” di tengah pergeseran nilai dan krisis keteladanan.
Dalam perspektif fiqih, pahlawan bukanlah orang yang dielu-elukan, tetapi yang berjuang menegakkan maqasid syariah tujuan luhur syariat: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan martabat manusia.
Gus Dur menjalankan kelima tujuan itu tanpa menghunus senjata. Ia menjaga agama dengan menegakkan Islam yang rahmah, bukan marah. Ia menjaga jiwa manusia dengan menolak kekerasan atas nama agama. Ia menjaga akal dengan memuliakan ilmu dan kebebasan berpikir. Ia menjaga harta dan martabat bangsa dengan melawan korupsi dan diskriminasi.
Dalam konteks fiqih al-hadlarah (fiqih peradaban), Gus Dur adalah mujtahid sosial. Ia menafsirkan kembali hukum Islam agar relevan dengan realitas modern dan kebangsaan Indonesia.
Bagi Gus Dur, menjadi muslim yang taat tidak berarti menolak kemajemukan, melainkan merawatnya sebagai amanah. Dalam istilahnya sendiri, “Islam datang bukan untuk menguasai, tapi untuk memanusiakan.”
Karena itu, dari kacamata fiqih, Gus Dur bukan sekadar ulama, tapi mujahid peradaban pejuang moral yang berijtihad di tengah pluralitas.
Gus Dur memahami manusia bukan sebagai objek kekuasaan, melainkan subjek kemanusiaan. Pemikirannya sejalan dengan eksistensialisme humanistik: bahwa kebebasan, kesetaraan, dan tanggung jawab adalah inti eksistensi.
Dalam banyak tulisan dan kebijakannya, Gus Dur menolak dehumanisasi dalam bentuk apa pun. Ia menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, membela minoritas Ahmadiyah, dan membuka ruang dialog lintas iman.
Secara filosofis, langkah-langkah itu mencerminkan gagasan humanisme teologis pandangan bahwa setiap manusia memiliki nilai karena diciptakan Tuhan, bukan karena suku, agama, atau jabatan.
Dalam kerangka ini, kepahlawanan tidak diukur dari kemampuan memimpin perang, melainkan dari keberanian menegakkan kemanusiaan di tengah ketakutan kolektif. Gus Dur adalah pahlawan karena ia berani sendirian di saat banyak orang memilih diam.
Seperti filsuf Martin Buber yang mengatakan, “Aku menjadi Aku karena Engkau,” Gus Dur menegakkan identitas kemanusiaan melalui pengakuan terhadap “yang lain”. Ia membebaskan Islam dari klaim eksklusif, menjadikannya agama dialog, bukan dominasi.
Dalam konteks hukum positif, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Syarat utama seorang pahlawan adalah “berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara” serta “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat bangsa.”
Jika parameter itu digunakan, Gus Dur memenuhi kriteria secara substantif dan historis. Sebagai presiden keempat, ia mengembalikan kepercayaan rakyat pada demokrasi setelah rezim otoritarian. Ia menghapus diskriminasi etnis, menguatkan supremasi sipil atas militer, dan membangun fondasi kebebasan pers yang hari ini kita nikmati.
Namun di balik itu, pengakuan negara terhadap Gus Dur juga memiliki makna hukum yang lebih dalam: bahwa kepahlawanan tidak selalu identik dengan heroisme militer, melainkan juga perjuangan moral dan konstitusional.
Dalam kerangka konstitusi, Gus Dur menjadi simbol rule of law with humanity hukum yang menegakkan keadilan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Ia menunjukkan bahwa penegakan hukum tanpa etika hanyalah kekuasaan yang dingin.
Namun, perlu kita akui, gelar pahlawan di Indonesia sering terjebak dalam politisasi. Banyak tokoh besar yang belum diakui karena tafsir sejarah yang bias atau kepentingan politik sesaat.
Dalam konteks itu, penganugerahan gelar kepada Gus Dur justru menjadi koreksi moral terhadap pola lama. Ia menandai pergeseran paradigma dari pahlawan senjata menuju pahlawan nurani.
Namun di sisi lain, publik juga mesti waspada agar gelar tersebut tidak dijadikan kultus individu. Gus Dur sendiri, dalam kesederhanaannya, mungkin akan menolak disakralkan. Ia lebih senang disebut pekerja kemanusiaan ketimbang pahlawan.
Sebagaimana ia pernah berkata, “Saya bukan orang suci. Saya hanya berusaha jujur.” Kalimat ini menjadi kritik paling tajam terhadap budaya politik kita yang masih gemar memuja figur, bukan meneladani nilai.
Pahlawan yang Mengajarkan Kesadaran
Gus Dur mengajarkan bahwa kepahlawanan bukanlah status hukum, melainkan kesadaran moral. Ia menolak kekerasan, memperjuangkan toleransi, dan menegakkan demokrasi berbasis welas asih. Dalam fiqih, ia seorang mujtahid; dalam filsafat, seorang humanis; dalam hukum positif, seorang demokrat sejati.
Ketika bangsa ini semakin gamang mencari teladan, Gus Dur menunjukkan jalan sunyi: menjadi manusia yang membebaskan manusia lain. Dan mungkin, di situlah makna terdalam dari kepahlawanan sejati bukan di monumen batu, tetapi di nurani yang tak pernah berhenti berpihak pada kemanusiaan.
***
*) Oleh : Moh Nur Fauzi, S.H.I., M.H., Dosen Filsafat Ilmu dan Studi Islam Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |