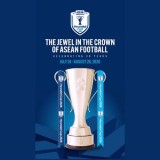TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Bahasa Arab selama ratusan tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi pesantren di Indonesia. Ia bukan sekadar bahasa asing, tetapi bahasa ilmu, bahasa doa, bahasa tradisi, bahkan bagian dari identitas keislaman Nusantara. Namun, memasuki era digital yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, posisi bahasa Arab mengalami transformasi besar.
Dari ruang-ruang pesantren yang penuh adab, ia kini menyeberang ke dunia aplikasi, kelas virtual, platform pembelajaran, hingga media sosial yang ritmenya bergerak cepat. Perubahan inilah yang melahirkan fenomena menarik: perjalanan bahasa Arab dari pesantren ke platform digital.
Transformasi ini tidak hanya sekadar perubahan alat belajar, tetapi juga perubahan paradigma. Thomas Kuhn dalam pemikiran tentang perubahan paradigma menyebut bahwa suatu sistem pengetahuan akan bergeser ketika metode lama tak lagi sepenuhnya menjawab tantangan zaman.
Pembelajaran bahasa Arab tradisional yang dulu bertumpu pada hafalan, talaqqi, dan pembacaan kitab kuning kini bertemu dengan dunia baru yang berpusat pada kemandirian belajar, fleksibilitas, serta interaksi virtual.
Generasi digital yang terhubung oleh internet tidak lagi menunggu pengajaran di ruang kelas; mereka langsung belajar dari video pendek, aplikasi adaptif, atau mentor dari berbagai negara Arab yang mereka temukan secara daring.
Fenomena ini menciptakan bentuk baru demokratisasi ilmu. Paulo Freire menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses pembebasan dan partisipasi aktif manusia dalam mencari pengetahuan.
Kini, masyarakat awam yang dulu merasa jauh dari tradisi bahasa Arab mulai menemukan akses belajar yang mudah. Mereka belajar mufradat melalui aplikasi, memahami gramatika lewat video penjelasan, dan mendengarkan percakapan bahasa Arab melalui podcast.
UNESCO pada 2023 mencatat peningkatan signifikan akses pembelajaran bahasa melalui platform digital, termasuk bahasa Arab, terutama di Asia Tenggara. Digitalisasi memberi ruang yang selama ini tidak dimiliki oleh masyarakat non-pesantren.
Namun, transformasi besar selalu membawa tantangan baru. Neil Postman telah mengingatkan bahwa teknologi tak hanya mempermudah akses, tetapi juga mengubah cara manusia memahami pengetahuan.
Banyak konten bahasa Arab yang beredar cepat di media sosial tetapi dangkal secara metodologis. Muncul tren “belajar bahasa Arab kilat” yang lebih menonjolkan kecepatan daripada kedalaman.
Padahal, dalam tradisi pesantren, bahasa Arab bukan sekadar keterampilan linguistik, tetapi jalan menuju adab, makna, dan kebijaksanaan. Agenda memperluas akses ilmu tidak boleh menghilangkan hakikat pembelajaran yang sesungguhnya.
Dalam ruang digital, muncul pula metode-metode baru. Pendekatan komunikatif yang dipopulerkan Dell Hymes menjadi salah satu metode paling banyak digunakan. Pelajar kini tidak hanya menghafal kaidah nahwu-sharaf, tetapi diajak berbicara, mendengar, dan memahami bahasa Arab sebagai alat komunikasi. Metode ini sangat selaras dengan karakter generasi muda yang belajar melalui praktik langsung, bukan pola ceramah satu arah.
George Siemens melalui teori connectivism-nya semakin memperkuat legitimasi bahwa belajar di era digital adalah proses membangun jejaring pengetahuan bersama teknologi. Aplikasi modern bahkan mampu menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan performa pengguna, menciptakan pengalaman yang personal dan adaptif.
Menariknya, banyak lembaga pesantren merespons perubahan ini secara kreatif. Pesantren Lirboyo, Sidogiri, hingga Darussalam Banyuwangi telah mengembangkan sistem pembelajaran digital dengan tetap mempertahankan tradisi keilmuan mereka.
Gus Dur dalam gagasan pribumisasi Islam memberi fondasi penting bahwa tradisi dan modernitas tidak perlu dipertentangkan; keduanya bisa berjalan seiring selama substansi keilmuan tetap dijaga. Itulah yang kini terlihat di banyak pesantren: mereka tidak menolak digitalisasi, tetapi menempatkannya sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu ke lebih banyak orang tanpa kehilangan identitas.
Namun, pembelajaran digital tidak boleh mengabaikan nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Syed Naquib al-Attas mengingatkan bahwa pendidikan sejati adalah proses ta’dib penanaman adab dan moralitas.
Dalam dunia digital yang serba cepat, nilai-nilai inilah yang berisiko hilang. Pelajar mungkin lebih cepat menguasai kosakata, tetapi belum tentu memahami etika dalam membaca teks suci atau menghormati guru.
Oleh karena itu, sinergi antara pesantren dan platform digital menjadi penting agar pengetahuan tetap memiliki akar, bukan hanya daun-daun informasi yang berhamburan.
Di balik peluang besar digitalisasi, tantangan lain adalah kesenjangan infrastruktur. Masyarakat urban memiliki akses luas terhadap internet dan perangkat digital, sementara masyarakat pelosok tidak selalu memiliki kesempatan yang sama.
Tanpa kebijakan yang inklusif, digitalisasi justru bisa memperlebar jurang akses pembelajaran bahasa Arab. Padahal, tujuan utama pendidikan Islam adalah keadilan dan keterjangkauan pengetahuan.
Kini, tantangan terbesar bukan lagi apakah pesantren akan bertahan menghadapi digitalisasi, tetapi bagaimana keduanya berjalan berdampingan. Pesantren menyimpan tradisi keilmuan, kedalaman makna, dan etika belajar yang menjadi ruh pendidikan Islam.
Platform digital menyediakan ruang yang luas, dinamis, dan menjangkau masyarakat awam dengan sangat cepat. Jika keduanya dipadukan, pembelajaran bahasa Arab tidak hanya akan tetap hidup, tetapi justru berkembang lebih kuat dan relevan dengan zaman.
Sebagaimana pandangan Alvin Toffler tentang revolusi informasi, arus pengetahuan hari ini menuntut kemampuan adaptasi, bukan sekadar konservasi tradisi. Dalam konteks Indonesia, pembelajaran bahasa Arab yang bergerak dari pesantren ke platform digital adalah bagian dari perubahan besar menuju masyarakat pengetahuan. Ruang belajar semakin terbuka, batas-batas semakin cair, dan masyarakat semakin mudah mengakses ilmu yang dulu hanya berada di tangan sebagian kalangan.
Perjalanan ini bukan soal mengganti pesantren dengan platform, tetapi memperluas ruang belajar untuk semua orang. Bahasa Arab kini hadir di berbagai tempat: di kelas-kelas digital, aplikasi, ruang pesantren, dan bahkan percakapan ringan di media sosial.
Jik pembelajaran ini terus dipandu oleh nilai, adab, dan metodologi yang benar, maka masa depan bahasa Arab di Indonesia akan semakin cerah, bukan sebagai bahasa masa lalu, tetapi sebagai bahasa yang terus bergerak bersama zaman dan bersama masyarakat yang menghidupkannya. (*)
***
*) Oleh : Siti Hasanah, S.H.I., Guru Fikih dan Bahasa Arab MTs Al-Huda Sukorejo Bangorejo Banyuwangi.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |