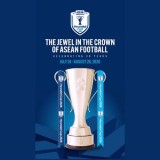TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Fenomena boikot terhadap sejumlah program televisi, termasuk Trans7, kembali ramai diperbincangkan di ruang digital. Publik bereaksi keras setelah muncul tayangan yang dianggap menyinggung nilai keagamaan.
Dalam hitungan jam, tagar #BoikotTrans7 memuncaki trending topic di media sosial X (Twitter), menjadi bentuk protes moral warga digital terhadap isi siaran yang dinilai tak sejalan dengan semangat dakwah. Reaksi cepat ini memperlihatkan bagaimana kekuatan publik kini mampu mengguncang dunia media hanya dengan tekanan dari gawai di tangan.
Fenomena tersebut memperlihatkan adanya perubahan besar dalam pola komunikasi keagamaan di era digital. Jika dahulu dakwah disampaikan di masjid, pesantren, atau forum pengajian, kini dakwah telah bertransformasi menjadi produk media yang dikonsumsi secara masif di televisi dan media sosial.
Media, termasuk Trans7, bukan lagi sekadar penyampai informasi, tetapi pembentuk opini dan persepsi publik terhadap agama. Inilah era ketika dakwah bersaing dengan hiburan, sensasi, dan algoritma.
Perubahan ini membawa dua sisi yang kontras. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang luas bagi demokratisasi dakwah. Siapa pun bisa berdakwah, menyebarkan nilai kebaikan, dan berinteraksi langsung dengan publik tanpa batas geografis. Namun di sisi lain, dakwah juga menjadi rentan terhadap polarisasi dan penyalahgunaan makna.
Boikot bisa lahir bukan dari substansi pesan, tetapi karena salah tafsir terhadap potongan video atau konteks yang tak utuh. Dunia digital menjadikan kebenaran bersifat relatif, sementara emosi publik berjalan lebih cepat daripada klarifikasi.
Dalam perspektif teori komunikasi massa, Marshall McLuhan pernah menegaskan bahwa the medium is the message media itu sendiri memengaruhi cara orang memahami realitas. Televisi, YouTube, atau TikTok bukan sekadar alat penyampai, melainkan lingkungan yang membentuk persepsi dan emosi penontonnya (McLuhan, 1964). Karena itu, pesan dakwah yang disampaikan lewat media tidak lagi bebas nilai. Ia terikat pada logika industri, algoritma, dan kepentingan audiens.
Dalam konteks dakwah Islam, hal ini menuntut kesadaran terhadap prinsip adab al-tablig atau etika penyampaian pesan. Dakwah yang baik tidak hanya menyampaikan isi, tetapi juga memperhatikan cara, konteks, dan niat di baliknya.
Al-Quran mengajarkan agar dakwah dilakukan bil hikmah wa al-mau‘izhah al-hasanah dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Artinya, setiap bentuk komunikasi dakwah, termasuk melalui media massa, harus memperhatikan sensitivitas publik dan mengedepankan kemaslahatan.
Namun realitas media sering kali berjalan dengan logika yang berbeda. Rating, sensasi, dan klik menjadi faktor dominan dalam menentukan tayangan. Dalam situasi seperti itu, pesan dakwah berisiko kehilangan substansinya dan berubah menjadi komoditas.
Fenomena boikot terhadap Trans7 dapat dibaca sebagai bentuk kritik sosial terhadap distorsi nilai dakwah dalam industri media. Publik bereaksi bukan semata-mata karena menolak program, tetapi karena merasa etika dakwah telah tergelincir di tangan media yang terlalu mengejar popularitas.
Gerakan boikot sendiri menimbulkan dua kutub pandangan. Kelompok pertama mendukung boikot sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar di era digital. Mereka menilai, ketika media melanggar nilai-nilai Islam atau mempermainkan simbol agama, maka publik berhak menegur melalui kekuatan sosial digital. Dalam pandangan ini, boikot adalah ekspresi moral untuk mengingatkan media agar kembali pada fungsi edukatif dan religiusnya.
Namun kelompok lain memandang boikot sebagai reaksi emosional yang berlebihan. Mereka berargumen bahwa dakwah seharusnya mendidik, bukan menghakimi. Reaksi publik yang terlalu cepat tanpa klarifikasi bisa menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman.
Dalam pandangan ini, budaya boikot atau cancel culture justru menghambat komunikasi dua arah dan mempersempit ruang dialog. Dakwah yang sejati seharusnya menumbuhkan kesabaran dan kebijaksanaan, bukan perpecahan.
Perdebatan dua kutub ini mencerminkan kompleksitas umat Islam di tengah arus komunikasi digital. Di satu sisi, masyarakat semakin kritis terhadap representasi agama di media. Di sisi lain, emosi digital sering kali mengaburkan nilai tabayyun atau klarifikasi.
Tantangan utama bagi umat Islam bukan lagi bagaimana berdakwah, tetapi bagaimana menjaga adab komunikasi di ruang maya yang serba cepat dan bising.
Fenomena boikot sebenarnya bisa menjadi momentum positif bila dikelola secara bijak. Pertama, bagi pihak media seperti Trans7, boikot seharusnya dibaca sebagai umpan balik publik, bukan ancaman. Ini kesempatan untuk memperbaiki tata kelola program dakwah agar lebih etis, kontekstual, dan berorientasi pada nilai kemaslahatan.
Media bisa menggandeng ulama, akademisi, dan komunikator Islam untuk merancang format siaran yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mendidik secara moral.
Kedua, bagi masyarakat Muslim, era digital menuntut kecerdasan literasi media. Tidak semua informasi di media sosial mencerminkan kebenaran utuh. Sikap tabayyun memverifikasi sebelum bereaksi adalah kunci untuk menghindari fitnah dan disinformasi. Umat perlu menyadari bahwa dakwah yang baik juga memerlukan etika berkomentar, berbagi, dan bereaksi di ruang publik digital.
Ketiga, bagi para dai dan komunikator Islam, era digital membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan dakwah. Namun, peluang itu juga menuntut inovasi dan kepekaan. Dakwah yang kaku, eksklusif, dan monoton sulit diterima oleh generasi digital yang terbiasa dengan visual, interaksi cepat, dan bahasa ringan. Karena itu, dai perlu memahami logika media tanpa kehilangan nilai ruhani dakwah.
Fenomena boikot Trans7 tidak seharusnya hanya dilihat sebagai konflik antara media dan publik Muslim. Lebih dari itu, ia adalah cermin dari ujian etika komunikasi Islam di era digital. Umat, media, dan para dai sama-sama diuji: apakah mampu menjaga adab dakwah di tengah derasnya arus informasi, atau justru terjebak dalam pusaran reaksi yang tak terkendali.
Dakwah di era digital bukan lagi sekadar soal menyebarkan pesan kebaikan, tetapi juga menjaga cara menyampaikannya. Media harus bertanggung jawab pada konten yang ditayangkan, sementara masyarakat harus dewasa dalam menanggapi.
Boikot, bila dilakukan dengan bijak, dapat menjadi sarana koreksi moral. Namun jika dilakukan dengan amarah, ia justru menjauhkan semangat dakwah dari nilai rahmatan lil ‘alamin.
Era digital menghadirkan tantangan baru bagi komunikasi Islam mulai dari kecepatan informasi, polarisasi opini, hingga banjir konten yang sulit diverifikasi.
Di tengah situasi itu, Islam mengajarkan keseimbangan antara amar ma’ruf dan hikmah, antara kritik dan kasih sayang, antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Boikot mungkin berhenti pada tagar, tetapi pesan dakwah sejati harus terus hidup dalam tindakan, keteladanan, dan kebijaksanaan komunikasi umat.
***
*) Oleh : Moh Nur Fauzi, S.H.I., M.H. Dosen Studi Islam dan Filsafat Ilmu Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |