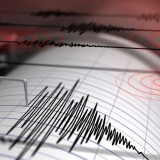TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Selama dua dekade pascareformasi, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi penanda utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Meski tampak sebagai wujud kemajuan demokrasi di tingkat lokal, kenyataannya sistem ini dibarengi oleh melonjaknya beban biaya politik yang sering kali tidak sejalan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh banyak daerah.
Di sinilah muncul ironi: kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun dukungan anggarannya tetap sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Seiring waktu, muncul beragam kritik terhadap sistem ini, terutama terkait mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Besarnya biaya tersebut tidak hanya mendorong praktik-praktik politik transaksional, tetapi juga memperbesar risiko korupsi anggaran dan penyalahgunaan wewenang setelah menjabat.
Di sisi lain, banyak daerah di Indonesia masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadi sumber utama dalam struktur keuangan daerah.
Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih dibiayai melalui transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih sebatas formalitas, belum menyentuh aspek substansial terutama dalam hal pengelolaan keuangan secara mandiri.
Ketika kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung namun daerah yang dipimpinnya belum memiliki kemandirian fiskal, terjadi ketidaksesuaian mendasar antara cita-cita demokrasi dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam situasi ini, wacana untuk mengembalikan kewenangan pemilihan kepala daerah kepada DPRD kembali mencuat sebagai alternatif yang dinilai lebih rasional dan efisien, khususnya bagi daerah yang masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara derajat ketergantungan fiskal suatu daerah dan relevansi model pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, dengan mengacu pada perspektif politik anggaran serta teori demokrasi delegatif.
Aaron Wildavsky (1964), dalam karya The Politics of the Budgetary Process, menegaskan bahwa proses penganggaran bukan sekadar kegiatan administratif yang objektif, melainkan arena kontestasi politik tempat berbagai aktor bersaing menyuarakan kepentingan, memperebutkan kekuasaan, dan menegosiasikan preferensi.
Dalam konteks lokal, dinamika pengelolaan anggaran menjadi cerminan hubungan antara eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD), yang pada gilirannya menunjukkan arah prioritas kebijakan dan potensi transaksi kekuasaan.
Pilkada langsung memang memberikan kekuatan lebih besar kepada kepala daerah dalam mengatur keuangan daerah, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi penyimpangan anggaran, terutama karena tekanan politik selama proses elektoral.
Dari sudut pandang ekonomi politik, Richard Musgrave (1959) menegaskan bahwa kapasitas suatu daerah untuk membiayai pengeluaran publik dari sumbernya sendiri merupakan tolok ukur utama dari otonomi fiskal. Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, pemerintah daerah cenderung mengandalkan transfer fiskal dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ketergantungan semacam ini menciptakan ilusi kemandirian: secara administratif daerah tampak otonom, namun secara fiskal sangat tergantung. Situasi ini memunculkan dilema ketika kepala daerah yang dipilih secara langsung dihadapkan pada keterbatasan anggaran dalam mewujudkan janji-janji kampanye secara mandiri.
Guillermo O'Donnell, seorang ilmuwan politik asal Argentina, pada tahun 1994 memperkenalkan konsep demokrasi delegatif untuk menjelaskan kondisi di mana pemilihan umum diselenggarakan secara sah dan terbuka, namun pasca-pemilihan, pemimpin terpilih cenderung menjalankan pemerintahan secara otoritatif tanpa kontrol institusional yang memadai.
Dalam kerangka ini, pemimpin merasa memperoleh mandat langsung dari rakyat, tetapi kerap mengabaikan prinsip akuntabilitas yang semestinya dijalankan melalui sistem perwakilan.
Fenomena serupa dapat ditemukan dalam praktik pemerintahan lokal di Indonesia, khususnya pada kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung namun menguasai kebijakan anggaran secara dominan, meski sebagian besar dana daerah masih bersumber dari transfer fiskal pusat.
Secara elektoral mereka memiliki legitimasi yang kuat, tetapi minimnya otonomi fiskal membuat mereka rentan terhadap tekanan kompromi politik dalam proses penyusunan APBD. Dalam situasi ini, model pilkada langsung mulai menunjukkan karakteristik demokrasi delegatif sebagaimana digambarkan oleh O'Donnell yakni tampak demokratis secara prosedural, tetapi lemah dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas substantif.
Atas dasar itu, dalam kondisi tertentu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif model demokrasi delegatif yang lebih terkonsolidasi, asalkan disertai dengan penguatan fungsi pengawasan legislatif serta peningkatan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Kendati demikian, pendekatan ini juga tidak lepas dari tantangan, seperti potensi menguatnya dominasi elit politik dan menyusutnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal.
Ketergantungan Fiskal Daerah: Fakta dan Dampaknya
Ketergantungan fiskal daerah di Indonesia merupakan persoalan struktural yang masih belum terselesaikan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Meskipun desentralisasi fiskal telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, pada praktiknya sebagian besar daerah belum mampu membiayai kebutuhan pembangunan tanpa sokongan dana dari pemerintah pusat.
Pertama, Ketergantungan Fiskal dan Mahal Biaya Demokrasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu tonggak penting dari proses reformasi yang bertujuan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, banyak daerah di Indonesia belum mampu menopang sistem demokrasi ini secara optimal. Ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota hanya berkisar antara 10 hingga 25 persen. Bahkan di sejumlah daerah terpencil, angka ini turun hingga di bawah 10 persen.
Artinya, lebih dari 70 persen kebutuhan pembiayaan daerah masih mengandalkan transfer fiskal dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan lainnya.
Sebagai ilustrasi, Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 hanya mampu mengumpulkan PAD sekitar Rp15,1 miliar, yang mewakili 5,2 persen dari total APBD sebesar Rp289 miliar (BPS dan DJPK, 2023).
Dengan tingkat kemiskinan yang melebihi 30 persen dan kapasitas perekonomian daerah yang rendah, ruang fiskal yang dimiliki sangat terbatas. Meski begitu, pemilihan kepala daerah tetap harus digelar secara langsung, yang membutuhkan biaya kampanye dan logistik yang besar beban yang sulit ditanggung oleh kemampuan anggaran daerah.
Contoh lain terlihat di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, yang pada tahun 2023 mencatat PAD hanya sekitar Rp8 miliar, jauh di bawah rata-rata nasional. Bila dibandingkan dengan estimasi ongkos politik pilkada yang dapat mencapai puluhan miliar rupiah (ICW, 2021), ketimpangan ini menjadi tekanan besar bagi kepala daerah terpilih.
Kondisi ini kerap memunculkan praktik “balas jasa” kepada penyokong politik maupun manipulasi dalam pengelolaan anggaran sebagai jalan pintas mempertahankan kekuasaan.
Sebaliknya, Kota Surabaya menjadi contoh positif dari daerah yang relatif mandiri secara fiskal. Pada tahun 2023, kota ini berhasil mengumpulkan PAD lebih dari Rp5 triliun atau sekitar 49 persen dari total APBD yang mencapai Rp10,1 triliun.
Tingkat kemandirian fiskal yang tinggi tersebut mendukung pelaksanaan pilkada langsung yang lebih berkualitas, dengan potensi penyimpangan yang lebih kecil berkat tata kelola anggaran yang transparan serta keterlibatan dan pengawasan masyarakat yang aktif.
Di sisi lain, keterlibatan publik dalam tahapan perencanaan maupun pengawasan anggaran daerah masih sangat terbatas. Proses pembahasan APBD kerap berlangsung secara tertutup, kurang dapat diakses oleh warga, dan minim akuntabilitas (FITRA, 2020).
Idealnya, demokrasi lokal menjadi ruang partisipasi aktif masyarakat, namun dalam praktiknya justru berisiko dikuasai oleh kelompok elite politik. Hal ini terjadi ketika pemilihan kepala daerah dijadikan sebagai sarana investasi politik yang mahal, yang kemudian ‘dibayar kembali’ melalui distribusi proyek atau akses terhadap anggaran publik.
Dalam kondisi seperti itu, kualitas tata kelola pemerintahan daerah tidak mengalami kemajuan, bahkan bisa mengalami kemunduran. Jika pilkada langsung hanya dijalankan sebagai ritual prosedural belaka, tanpa disertai penguatan integritas institusional, keterbukaan anggaran, dan pengawasan publik yang memadai, maka substansi demokrasi lokal menjadi semakin lemah.
Tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi telah memicu wacana mengenai penyesuaian biaya politik melalui mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Gagasan utamanya adalah: ketika suatu daerah belum memiliki kemandirian fiskal dalam mengelola pendapatan dan belanjanya, maka sistem pemilihan tidak langsung dinilai lebih efisien secara anggaran.
Selain itu, model ini diyakini dapat meningkatkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif karena kepala daerah dipilih dari kalangan elite politik lokal yang telah terlibat dalam proses legislatif.
Gagasan tersebut sejalan dengan hasil kajian Tjiptoherijanto (2016), yang menemukan bahwa daerah dengan tingkat PAD rendah dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pusat cenderung lebih rentan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada langsung. Di wilayah-wilayah tersebut, pilkada langsung justru menjadi beban fiskal tambahan tanpa diimbangi oleh akuntabilitas politik dan keuangan yang memadai.
Tantangan Kelembagaan dalam Politik Anggaran dan Pilkada
Secara normatif, pemilihan langsung kepala daerah dirancang untuk memperkuat demokrasi lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Namun pada kenyataannya, proses ini sering menimbulkan distorsi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Politik anggaran berubah menjadi arena tawar-menawar antara calon kepala daerah, elite partai, dan kelompok kepentingan lokal yang memiliki sumber daya dan pengaruh. Situasi ini semakin diperparah oleh lemahnya fungsi pengawasan institusi publik serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas fiskal di sejumlah daerah.
Meski demikian, pemilihan melalui DPRD juga tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Model ini berpotensi mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite serta menurunkan tingkat keterlibatan publik dalam menentukan kepemimpinan lokal.
Kekhawatiran bahwa mekanisme ini akan memperkuat cengkeraman oligarki lokal tidak dapat diabaikan, terutama di daerah di mana DPRD belum menunjukkan kualitas integritas dan representasi yang layak (Hadiz & Robison, 2017).
Dengan demikian, perubahan sistem pemilihan kepala daerah perlu dipertimbangkan secara kontekstual. Evaluasi terhadap kapasitas fiskal dan kondisi kelembagaan daerah harus menjadi landasan utama, bukan semata-mata didorong oleh keinginan untuk efisiensi administratif.
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar, baik dari sisi pembiayaan oleh negara maupun dari biaya politik yang harus ditanggung oleh para kandidat.
Para calon kepala daerah kerap harus menggelontorkan dana mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membayar mahar partai, membangun citra elektoral, serta mengamankan dukungan politik.
Selain beban biaya penyelenggaraan, proses kampanye juga menyerap anggaran yang sangat tinggi dari para kandidat. Banyak calon kepala daerah harus menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk operasional kampanye, menjalin kesepakatan dengan partai politik, dan mengelola persepsi publik terhadap dirinya.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah menyinggung tingginya ongkos politik dalam pilkada. Dalam pidatonya pada peringatan HUT Partai tahun 2024, ia menyatakan bahwa “Pilkada ini, bukan hanya kalah, menang pun terasa menyakitkan.”
Hal itu, menurutnya, disebabkan oleh beban finansial yang luar biasa besar, dan meskipun menang, para kandidat tetap harus memenuhi beragam janji politik. Ungkapan tersebut menunjukkan tekanan yang dihadapi kepala daerah pasca-pilkada, terutama di wilayah yang belum memiliki kemandirian fiskal yang cukup.
Kondisi ini menyebabkan banyak kepala daerah terpilih akhirnya terjebak dalam praktik kompromi politik pasca-pemilihan. Bentuknya bisa berupa penyaluran proyek ke wilayah tertentu sebagai bentuk timbal balik politik, pemberian akses proyek kepada para pendukung kampanye, hingga penyalahgunaan anggaran daerah demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Praktik-praktik ini merusak esensi anggaran publik sebagai instrumen pembangunan dan pelayanan masyarakat, melemahkan kualitas perencanaan daerah, serta memperbesar potensi terjadinya korupsi.
Dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kepala daerah umumnya memperoleh legitimasi politik yang lebih kuat dibandingkan DPRD karena mandat yang mereka peroleh berasal langsung dari rakyat. Namun, hal ini berdampak pada ketidakseimbangan distribusi kekuasaan.
Kepala daerah cenderung memiliki dominasi lebih besar dalam pengambilan keputusan anggaran, sehingga dalam banyak kasus, keterlibatan DPRD hanya bersifat prosedural tanpa peran yang signifikan.
Sejumlah studi mengungkapkan bahwa relasi antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal lebih sering digerakkan oleh kepentingan pragmatis sesaat, ketimbang oleh mekanisme checks and balances yang sehat.
Penelitian yang dilakukan LIPI (2017) serta Antlöv, Wetterberg, dan Dharmawan (2016) menunjukkan bahwa kolusi antara kepala daerah dan DPRD kerap terjadi dalam proses penyusunan APBD, terutama jika kepala daerah telah mengamankan dukungan legislatif sejak masa pencalonan.
Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan yang kritis, DPRD dalam banyak situasi justru terlibat dalam praktik politik transaksional. Posisi dan pengaruh politik mereka sering kali dipertukarkan dengan proyek pembangunan, dana aspirasi, atau akses terhadap anggaran hibah dan bantuan sosial.
Lemahnya Kelembagaan Anggaran Daerah
Perencanaan anggaran di tingkat daerah masih jauh dari nilai-nilai transparansi dan partisipasi publik. Menurut laporan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA, 2020), dokumen penting seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), hingga APBD final kerap kali tidak tersedia secara terbuka bagi masyarakat. Akses informasi terhadap dokumen-dokumen tersebut masih sangat terbatas.
Proses pembahasan APBD di DPRD pun umumnya berlangsung secara tertutup, tanpa melibatkan unsur masyarakat sipil maupun kalangan akademisi. Dengan demikian, mekanisme pilkada langsung belum secara signifikan memperkuat institusi penganggaran di daerah.
Yang terjadi justru konsentrasi kekuasaan anggaran di tangan kepala daerah, bukan distribusi kekuasaan yang lebih adil dan akuntabel. Situasi ini membuka celah bagi praktik penyimpangan, manipulasi kebijakan anggaran, bahkan korupsi yang terorganisasi.
Rasionalisasi Pilkada Tidak Langsung: Solusi atau Kemunduran?
Gagasan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD kembali mencuat sebagai respons atas mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung, lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta masih kuatnya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Namun, wacana ini menimbulkan perdebatan yang tajam. Di satu sisi, terdapat argumentasi rasional yang mendukung model pemilihan tidak langsung; namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat menggerus kualitas demokrasi lokal dan memperkuat dominasi oligarki di tingkat daerah.
1. Argumen Rasionalisasi Pilkada Tidak Langsung
Sejumlah argumen kerap dikemukakan untuk mendukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pertama, dari sisi efisiensi pengeluaran politik, model ini dinilai lebih hemat biaya dibandingkan pilkada langsung yang menuntut anggaran besar, baik untuk penyelenggaraan maupun aktivitas kampanye.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tahun 2021, pelaksanaan pilkada langsung di satu kabupaten/kota bisa menelan dana hingga Rp25–30 miliar, yang sebagian besar dibebankan pada APBD. Dalam konteks fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada dana pusat, efisiensi anggaran menjadi pertimbangan utama.
Kedua, pemilihan oleh DPRD diyakini dapat mempererat hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif, mengingat kepala daerah terpilih berasal dari ruang politik yang sama, sehingga koordinasi kebijakan lebih mudah terwujud dan proses persetujuan anggaran dapat berjalan tanpa friksi yang berarti.
Ketiga, dari aspek stabilitas politik lokal, pemilihan langsung kerap melahirkan polarisasi tajam di tengah masyarakat, bahkan memicu konflik sosial horizontal. Pemilihan tidak langsung dinilai lebih tertutup dan cenderung menekan potensi disintegrasi tersebut.
Keempat, akuntabilitas kelembagaan dianggap lebih terukur ketika kepala daerah dipilih oleh
DPRD, karena mekanisme kontrol dilakukan melalui jalur institusional yang formal, bukan sekadar popularitas atau retorika kampanye.
2. Risiko dan Kekhawatiran yang Muncul
Meskipun tampak rasional, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap kualitas demokrasi di tingkat lokal. Pertama, model ini rentan memperkuat dominasi oligarki dan kecenderungan elitisme kekuasaan. Proses pemilihan bisa saja dimonopoli oleh segelintir elit partai dan pemilik modal yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan DPRD.
Pandangan ini senada dengan kritik Winters (2011) mengenai bentuk oligarki elektoral, yakni situasi di mana pemilu memang dilakukan, tetapi hasilnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan jaringan elit yang membatasi keterlibatan publik secara nyata.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat kehilangan peran langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya dan hanya menjadi penonton dalam proses politik yang menentukan arah pembangunan.
Kedua, risiko menurunnya partisipasi publik dan legitimasi demokrasi. Salah satu keunggulan utama dari pilkada langsung adalah keterlibatan masyarakat yang tinggi. Bila pemilihan dilakukan secara internal oleh DPRD, maka kepala daerah terpilih berpotensi kehilangan legitimasi, terutama di daerah yang lembaga legislatifnya belum sepenuhnya kredibel.
Ketiga, model ini dapat melemahkan akuntabilitas vertikal. Kepala daerah yang terpilih melalui DPRD cenderung berorientasi pada kepentingan kelompok politik yang mengusungnya, bukan pada masyarakat luas. Akibatnya, orientasi pelayanan publik dapat bergeser ke arah pemenuhan kepentingan elite, bukan kebutuhan warga.
Dalam menghadapi persoalan tersebut, dibutuhkan perancangan institusi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan kapasitas fiskal serta kualitas demokrasi lokal. Pilihan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD memang bukan solusi final, namun dapat dipertimbangkan sebagai opsi transisional bagi daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan kapasitas kelembagaan fiskal yang masih terbatas.
Meski demikian, perubahan mekanisme ini harus dibarengi dengan prasyarat yang ketat: mulai dari evaluasi mendalam terhadap kapasitas fiskal daerah, penguatan akuntabilitas dan transparansi lembaga legislatif, reformasi tata kelola anggaran yang partisipatif, hingga perluasan kanal keterlibatan publik meski pemilihan tidak dilakukan secara langsung. Di saat yang sama, peningkatan PAD dan kemandirian fiskal harus menjadi fokus utama, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Demokrasi lokal tak boleh sekadar dimaknai secara romantik lewat mekanisme pemilihan langsung yang mahal dan belum tentu efektif. Namun, mengejar efisiensi tanpa menjaga prinsip-prinsip partisipasi rakyat akan menjebak kita dalam jebakan elitisme kekuasaan.
Maka, yang dibutuhkan adalah sintesis antara legitimasi rakyat, efisiensi fiskal, dan tata kelola yang berkualitas sebuah demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial.
Oleh sebab itu, ada lima prasyarat penting yang harus dipenuhi bila wacana pilkada tidak langsung ingin dijalankan secara selektif dan bertanggung jawab. Pertama, diperlukan evaluasi mendalam atas kapasitas fiskal tiap daerah sebagai landasan pengambilan kebijakan. Pemerintah pusat perlu menyusun peta fiskal nasional untuk mengidentifikasi wilayah yang layak menerapkan sistem pemilihan tidak langsung secara terbatas dan bertahap.
Kedua, penguatan integritas dan peran strategis DPRD menjadi syarat mutlak. Bila kepala daerah dipilih oleh legislatif, maka DPRD harus mampu menjalankan fungsi representatifnya secara transparan dan akuntabel, agar kekuasaan tidak tersandera oleh kepentingan oligarki lokal.
Ketiga, reformasi tata kelola anggaran daerah sangat mendesak. Penyusunan dan pelaksanaan APBD harus dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat, serta diawasi secara ketat untuk mencegah praktik-praktik politisasi anggaran, baik dalam konteks pilkada langsung maupun tidak langsung.
Keempat, perlu dibuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pemilihan tidak langsung. Forum-forum aspirasi, mekanisme konsultasi terbuka, serta pengawasan masyarakat harus menjadi bagian dari proses untuk menjamin bahwa kepala daerah tetap memiliki akuntabilitas moral dan politik kepada warga.
Kelima, percepatan peningkatan PAD dan kemandirian fiskal perlu dijadikan agenda prioritas bersama. Pemerintah pusat dan daerah mesti bersinergi dalam memperluas basis penerimaan, memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta mengurangi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat.
Dengan demikian, wacana pilkada tak langsung tidak seharusnya hanya dilihat sebagai solusi teknokratis terhadap mahalnya biaya pemilu. Ia adalah refleksi atas kegagalan kolektif dalam membangun arsitektur daerah yang mandiri secara fiskal sekaligus matang secara demokratis.
Jika ongkos demokrasi lokal tak sepadan dengan kapasitas pengelolaan anggaran, maka perlu ada evaluasi menyeluruh bukan sekadar menyerahkan kewenangan kepada elit, tetapi memastikan bahwa demokrasi tidak kehilangan substansinya hanya karena tercekik oleh persoalan biaya. (*)
***
*) Oleh : Muhammad Sahlan, M.A, Fakultas Dakwah Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB).
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |