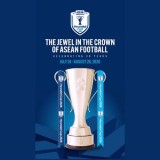TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pesantren memiliki posisi istimewa dalam lanskap pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Ia bukan sekadar lembaga pengajaran agama, melainkan juga ruang sosial tempat nilai, karakter, dan jaringan komunitas direproduksi dari generasi ke generasi.
Kementerian Agama (2024) mencatat terdapat 36.648 pesantren dengan lebih dari 5 juta santri, di mana 78 persen berada di wilayah pedesaan. Angka itu menegaskan pesantren sebagai denyut sosial yang menghidupi akar kultural masyarakat bawah.
Sejak masa awal, pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat. Ia tumbuh bukan dari proyek negara, melainkan dari kepercayaan umat terhadap figur kiai. Dari sini pesantren memainkan tiga peran utama: pusat dakwah, lembaga pendidikan, dan motor penggerak sosial.
Jika ditarik dari kacamata teori sosial Karl Marx, lembaga pendidikan termasuk pesantren dapat berfungsi sebagai alat reproduksi kelas sosial, yakni mempertahankan tatanan ideologis dan struktur kekuasaan yang sudah mapan.
Berbeda dari sekolah formal, santri di pesantren tidak hanya belajar kitab kuning. Mereka hidup dalam sistem komunal yang memperkuat solidaritas dan kemandirian. Banyak pesantren bahkan telah mengembangkan unit-unit ekonomi produktif seperti koperasi, pertanian, perdagangan, dan industri kreatif.
Kemenag mencatat lebih dari 6.800 pesantren memiliki unit usaha, terdiri atas 35% sektor pertanian, 27% perdagangan, dan 15% industri kreatif. Pesantren Al-Amin di Tasikmalaya, misalnya, berhasil mengembangkan industri bordir dengan omzet tahunan mencapai Rp1,2 miliar dan melibatkan masyarakat sekitar.
Begitu pula Pondok Modern Darussalam Gontor Putri di Ngawi yang mengelola lebih dari 20 unit usaha produktif, mempekerjakan 450 pekerja lokal dan menyumbang 22% dari total wakaf produktif nasional menurut data Badan Wakaf Indonesia.
Fakta ini memperlihatkan bahwa pesantren bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga pusat ekonomi rakyat yang mampu menggerakkan kesejahteraan berbasis spiritualitas.
Kepercayaan Sosial dan Kapital Simbolik
Keberadaan pesantren juga memiliki bobot sosial yang besar. Survei LSI (2023) menyebut 72% masyarakat desa lebih percaya pesantren dalam menyelesaikan konflik sosial dibanding aparat desa. Ini bukan angka kecil. Ia mencerminkan tingginya legitimasi sosial pesantren yang bersumber dari nilai-nilai moral dan keagamaan.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kepercayaan semacam itu disebut kapital simbolik nilai non-ekonomi yang membangun otoritas sosial. Pesantren, dengan aura kesalehan dan ketulusannya, menjadi institusi yang memproduksi dan mendistribusikan kepercayaan masyarakat. Maka tak berlebihan jika pesantren disebut sebagai agen perubahan sosial yang melampaui fungsi pendidikannya sendiri.
Pesantren tidak selalu steril dari kritik. Struktur kepemimpinan yang hierarkis dan berpusat pada figur kiai berpotensi melahirkan ketergantungan struktural di antara santri dan masyarakat.
Dalam bingkai Marx, relasi semacam ini bisa dimaknai sebagai bentuk reproduksi ideologi kelas di mana otoritas spiritual dapat bertransformasi menjadi kekuasaan sosial yang tidak seimbang.
Kasus kontroversial tayangan Xpose Uncensored di Trans7 yang menyorot praktik penghormatan santri terhadap kiai di Pesantren Lirboyo menjadi contoh bagaimana relasi kuasa dalam pesantren sering kali disalahpahami atau disederhanakan oleh media.
Tayangan itu memicu gelombang tagar #BoikotTrans7 yang digunakan lebih dari 137 ribu akun dalam 24 jam, hingga PBNU menempuh jalur hukum dan KPI menjatuhkan sanksi.
Kasus ini memperlihatkan dua hal sekaligus: pertama, adanya sensitivitas publik terhadap citra pesantren, dan kedua, bagaimana media bisa memperkuat stereotipe tentang relasi feodal di pesantren.
Pesantren dalam Pusaran Kapitalisme Modern
Di sisi lain, modernisasi juga membawa tantangan baru. Banyak pesantren kini masuk ke ranah bisnis modern, dari digitalisasi hingga ekspor produk halal. Meski positif, jika tidak disertai kesadaran kritis, transformasi ekonomi ini bisa menjauhkan pesantren dari nilai-nilai kesederhanaan dan egalitarianisme yang menjadi identitasnya.
Marx mungkin akan melihat fenomena ini sebagai bentuk integrasi lembaga tradisional ke dalam sistem kapitalisme, sementara teori kapital sosial dari Coleman dan Putnam justru memandangnya sebagai perluasan peran pesantren dalam membangun jaringan kepercayaan dan kemandirian masyarakat.
Secara teoritik, dua pandangan besar ini dapat disatukan untuk membaca realitas pesantren. Marx benar bahwa struktur sosial di pesantren bisa mereproduksi hierarki lama.
Namun Bourdieu, Coleman, dan Putnam juga benar bahwa pesantren menciptakan habitus sosial yang moderat, memperluas jaringan sosial, dan menjaga harmoni dalam masyarakat plural.
Pesantren hari ini bergerak di antara dua kutub: sebagai reproduktor nilai sosial lama sekaligus produsen kapital sosial baru. Dalam konteks inilah, pertanyaan “apakah pesantren mereproduksi kelas atau membangun kapital sosial?” tidak bisa dijawab secara hitam-putih.
Realitasnya, kedua hal itu berjalan beriringan tergantung pada bagaimana pesantren dikelola, nilai apa yang dijunjung, dan sejauh mana ia mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan ruh spiritualnya.
Pesantren adalah cermin masyarakat itu sendiri: ia bisa menjadi ruang pembebasan, tetapi juga bisa menjadi ruang reproduksi ketimpangan. Tugas kita bukan menuduh atau mengkultuskan, melainkan memastikan bahwa pesantren terus menjadi ruang transformasi sosial, bukan sekadar reproduksi kekuasaan kultural. (*)
***
*) Oleh : Zainul Ma’arif Assahrowardi, Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas KH. Mukhtar Syafaat.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |